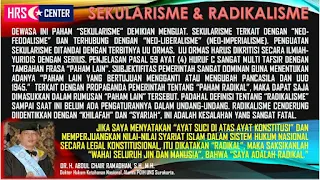HRS Center: Masa Depan Umat Vs Perkembangan Sekularisme & Neo - Feodalisme Di Era Neo - Liberalisme
Jum'at, 1 November 2019
Faktakini.net
MASA DEPAN UMAT VS PERKEMBANGAN SEKULARISME &
NEO-FEODALISME DI ERA NEO-LIBERALISME*
Dr. H. Abdul Chair Ramadhan, S.H., M.H.**
I. Prolog
Masa depan umat dan termasuk syariat Islam tidak lepas dari berbagai pengaruh
“perkembangan lingkungan strategis” (Balingstra) baik global, regional maupun
nasional. Di era globalisasi (neo-liberalisme) ini peranan agama Islam semakin
mendapatkan tantangan dan bahkan ancaman dengan menguatnya paham
sekularisme.
Terkait hal ini, Selo Sumardjan pernah menyampaikan pernyataan yang menarik bahwa pada tahun 2012 masyarakat Indonesia akan mengalami sekularisasi.
Dikatakan olehnya, dominasi ilmu pengetahuan dan teknologi dalam proses
industrialisasi akan menyebabkan peranan agama tereduksi dalam proses-proses
pengambilan keputusan di bidang sosial, ekonomi, politik dan sebagainya.
Tegasnya, dominasi ilmu pengetahuan dan teknologi akan menggeser pertimbangan-
pertimbangan agama dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kehidupan sosial.
Ternyata apa yang disampaikan oleh beliau menjadi kenyataan.
Sekularisme yang terjadi juga terkait dengan “neo-feodalisme” yang terhubung
dengan “neo-liberalisme”.
Penguatan sekularisme yang paling signifikan adalah
ditandai dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang (UU Ormas).
Perlu dicatat bahwa Indonesia bukankah menganut paradigma sekuler,
melainkan menganut paradigma “simbiotik”. Antara agama dan negara saling
membutuhkan dan bersinergi. Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah landasan konsitusional yang mengakui adanya hukum Agama (baca: Islam) dan dengannya negara harus menghormati dan mengambil nilai-nilai universalnya guna mewujudkan kemaslahatan dan menolak
kemudharatan.
II. Pembahasan
1. Sekularisme & Humanisme
Kita ketahui bahwa sekularisme berasal dan dilahirkan oleh Barat (Kristen).
Sistem pemikiran Barat cenderung “panteologis” yang menyebabkan konflik besar antara ilmu dan agama.
Konsekuensinya menimbulkan ‘perceraian’ antara ilmu dan agama, antara ilmu dan nilai.
Hampir semua cabang ilmu pengetahuan yang
berkembang di Barat muncul dari pendekatan non agama, jika bukan anti agama.
Pendekatan inilah yang menyebabkan lahirnya sekularisme.
Menurut Jose Casanova, paham sekularisme mengimplementasikan tiga
kemungkinan, sebagai berikut;
pertama, sekularisasi bermakna “diferensiasi” dan
“spesialisasi” yang memisahkan ranah agama dan negara, ekonomi dan ilmu pengetahuan.
Kedua, sekularisasi bermakna sebagai representasi merosotnya keyakinan agama, sehingga agama sama sekali kehilangan otoritasnya. Ketiga,
Sekularisasi bermakna “privatisasi” yang mempostulatkan bahwa agama diletakkan
dalam ranah privat.
Agama berada dalam posisi marginal dalam kekuasaan atau proses modernisasi.
Ditinjau dari perspektif tipologi kekuasaan organik, penguasa atas
nama negara memberikan dukungan dan akomodasi terhadap kelompok agama.
Penguasa menjadikan tokoh-tokoh agama, baik sebagai representasi kepentingan kelompok agama maupun sebagai badan penasehat negara. Agama hanya berstatus ‘simbolik’ dan ‘formalistik’ belaka.
Sekularisme sangat terkait dengan “renaisans”, suatu revolusi ilmu pengetahuan
dalam semangat non agama dan bahkan anti agama. Ilmu pengetahuan secara inheren bersifat bebas nilai. Terjadi gerakan kebangkitan kembali manusia dari kungkungan
“mitologi” dan “dogma-dogma”, dengan menjadikan manusia harus menguasai alam
semesta. Renaisans dipengaruhi oleh pandangan “antroposentrisme” (humanisme) yang beranggapan bahwa kehidupan tidak berpusat pada Tuhan, akan tetapi pada manusia.
Manusia yang menentukan nasibnya sendiri, bahkan manusia dapat menentukan (penentu) kebenaran.
Antroposentrisme muncul dengan datangnya
“rasionalisme” yang tidak percaya “hukum alam” (hukum kodrat/agama) bersifat
mutlak.
Dalam perspektif aliran hukum alam, keadilan
bersumber dari Ilahi Yang Maha Agung.
Aristoteles menggunakan istilah “keadilan Illahi” dalam pengertian bukan
merupakan produk sosial, tetapi merupakan kekuatan-kekuatan alami.
Sayyid Sabiq berpendapat bahwa keadilan itu dapat diwujudkan dengan menyampaikan setiap hak kepada yang berhak dan dengan melaksanakan hukum-hukum yang telah disyariatkan Allah serta dengan menjauhkan hawa nafsu melalui pembagian yang adil di antara sesama manusia.
2. Humanisme Menurut Islam
Kuntowijoyo menjelaskan bahwa humanisme Islam adalah “humanisme
teosentrik”, yaitu agama yang sangat mementingkan manusia sebagai tujuan, namun berbeda dengan prinsip-prinsip filsafat dan ajaran agama lain. Tegasnya, humanisme teosentrik adalah agama yang memusatkan dirinya pada keimanan terhadap Allah, namun juga mengarahkan perjuangannya untuk kemuliaan peradaban manusia.
Prinsip humanisme teosentrik inilah yang kemudian harus ditransformasikan sebagai
nilai yang dihayati dan dilaksanakan sepenuhnya dalam masyarakat dan budaya.
Selanjutnya, dikatakan dalam Islam terdapat ‘trilogi’ Iman, Ilmu dan Amal. Iman
berujung pada Amal, pada aksi. Dengan demikian, Islam menjadikan tauhid sebagai
pusat dari ‘orientasi nilai’. Adapun manusia sebagai tujuan dari ‘transformasi nilai’.
Dalam konteks inilah Islam disebut “rahmatan lil alamin”, rahmat untuk alam
semesta termasuk kemanusiaan.
Menurut Tolchah Hasan, Islam tidak hanya tampil sebagai sebuah agama
(religion), namun juga mewujud sebagai sebuah ‘peradaban’ (civilization) dan negara
(state). Dikatakan olehnya, barangkali inilah yang dimaksudkan “rahmatan lil
alamin” bagi “Dinul Islam”.
Terkait ilmu, Adian Husaini mengatakan bahwa dalam struktur ilmu pengetahuan terdapat hierarki ilmu pengetahuan. Pada lapisan atas terdapat ilmu-ilmu Ketuhanan melalui ilmu agama (baca: Islam), dan pada lapisan
kedia terdapat ilmu duniawi. Pada inti keilmuan terdapat asas kemanfaatan ilmu. Ilmu pengetahuan mencoba untuk menerangkan eksistensi Allah SWT sebagai ilmu
pengetahuan yang pertama. Menjelaskan hubungan (koneksitas) antara diri manusia dan Allah SWT.
Ilmu pengetahuan pada lapisan kedua mampu membingungkan
manusia, apabila tidak didukung dengan ilmu pengetahuan pertama. Oleh karena itu, ilmu pengetahuan kedua selalu terikat dan bergantung pada ilmu pengetahuan yang pertama.
Gambar dibawah ini mencoba memvisualisasikan keterhubungan trilogi iman-
ilmu-amal, tiga dimensi islam dan struktur ilmu pengetahuan menurut Islam.
Gambar. Perspektif Islam “Rahmatan Lil Alamin”
3. Tantangan Umat Islam
Tantangan yang kita hadapi terkait dengan pengaruh “Balingstra” adalah fase
baru feodalisme16 di era modern (neo-feodalisme). Fase ini ternyata tidak lepas dari cengkeraman “neo-imperialisme” dan keduanya saling bersinergi untuk kepentingan
(eksistensi) masing-masing. Kekuasaan yang digenggam oleh neo-feodalis ini tetap
dikendalikan oleh neo-imperialis. Dapat dikatakan, neo-feodalisme menjadi bagian
dan terkooptasi oleh neo-imperialisme. Dengan demikian tidak ada bedanya antara feodalisme dimasa tradisional dengan neo-feodalisme di era globalisasi saat ini.
3. Tantangan Umat Islam
Tantangan yang kita hadapi terkait dengan pengaruh “Balingstra” adalah fase
baru feodalisme16 di era modern (neo-feodalisme). Fase ini ternyata tidak lepas dari cengkeraman “neo-imperialisme” dan keduanya saling bersinergi untuk kepentingan
(eksistensi) masing-masing. Kekuasaan yang digenggam oleh neo-feodalis ini tetap
dikendalikan oleh neo-imperialis.
Dapat dikatakan, neo-feodalisme menjadi bagian
dan terkooptasi oleh neo-imperialisme. Dengan demikian tidak ada bedanya antara feodalisme dimasa tradisional dengan neo-feodalisme di era globalisasi saat Lebih lanjut, tidak menjadi jaminan bahwa dengan adanya perubahan sistem pemerintahan (ketatanegaraan) pada negara berkembang di era modern mampu
melepaskan dirinya dari para neo-feodalis dan neo-imperialis. Kekuasaan yang ada pada neo-feodalis ternyata sangat bergantung pada neo-imperialis. Neo-feodalis
tersebut sebagai ‘unit terpengaruh’, sedangkan neo-imperialis sebagai ‘unit pengaruh’
(eksplanasi).
Kekuasaan yang diperoleh sangat ditentukan oleh neo-imperialis
tersebut. Dalam mempertahankan kekuasaannya, kaum neo-feodalis tetap mengacu
kepada ajaran “trias politica”, namun dalam praktik pembagian kekuasaan itu telah direkayasa sedemikian rupa untuk kepentingan mempertahankan kekuasaannya.
Pada bidang sistem hukum, kaum neo-feodalis telah menjadikan “manusia untuk
hukum”, bukan sebaliknya. Pengaruh paham “positivism” menjadi dalil penguasa menegakkan hukum atas dasar kepastian belaka walaupun harus mencederai keadilan.
Kepentingan politik demikian “supreme” dan dengannya mampu mengintervensi
penegakan hukum. Hukum tidak lagi diposisikan sebagai sarana untuk mengubah
masyarakat guna mewujudkan kesejahteraan umum, namun telah menjelma sebagai
alat mempertahankan kekuasaan.
Pada sistem pemerintahan, berbagai posisi elemen pemerintahan diperuntukkan
hanya kepada kelompoknya dan menjadikannya sebagai perpanjangan ambisi
kekuasaan. Di sisi lain kepentingan pihak neo-imperialis turut pula memetik manfaat
melalui sejumlah regulasi yang menjauh dari prinsip keadilan sosial.
Kepentingan neo-imperialis melalui “actor non-state” harus diterjemahkan dalam sistem hukum ekonomi yang kemudian melahirkan produk perundang-undangan yang tidak pro rakyat. Jadi secara struktural tidak ada bedanya dengan sistem kekuasaan feodal (monarki). Kebijakan yang dibuat tentunya bersifat dualisme, di satu sisi
menguntungkan pihak penguasa dan pihak neo-imperialis namun di sisi lain menimbulkan kerugian dan derita nestapa rakyat.
Rakyat tidak menikmati pembangunan, yang mendapat manfaat adalah kelompok neo-feodalis dan neo-imperialis, hal ini sangatlah ‘miris’.
Budaya “materialisme” dan “hedonisme”
demikian kuat merasuk dalam diri kaum noe-feodalis dimasa kini. Eksploitasi
terhadap sumber daya alam demikian nyata, korupsi terjadi demikian ‘terstruktur’ dan ‘sistemik’, begitupun kriminalisasi terhadap lawan politik demikian ‘ofensif’ dan ‘masif’.
Penguasa bercorak neo-feodalis memposisikan dirinya sebagai ‘manusia
tertinggi’, walaupun tidak pernah menyatakan sebagai ‘penguasa religi’, namun melalui kekuasaannya mampu mendapatkan legitimasi atas kebijakannya dengan sejumlah fatwa dan/atau dukungan dari perkumpulan agama. Di sini terkonfirmasi
bahwa “Kitab Suci diposisikan di bawah konstitusi” demi sebuah ambisi.
Di era neo-feodalisme, peranan intelektual tradisional yang tidak berafiliasi dengan kekuasaan terpinggirkan, jikalau mereka berseberangan secara terbuka akan dimarginalkan dan tidak tertutup kemungkinan diterapkan sanksi hukum “kematian perdata”, terkecuali mau beradaptasi pastilah diakomodasi. Lain halnya dengan intelektual organik yang berhubungan dengan kekuasaan mereka akan dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan penguasa, lebih khusus lagi bagi neo-imperialis.
Saat ini, relatif sedikit intelektual - sebagaimana diharapkan oleh Noam
Chomsky - yang berada dalam posisi mengungkapkan kebohongan-kebohongan
pemerintah, menganalisis tindakan-tindakannya sesuai dengan penyebab, motif dan maksud yang tersembunyi.
Ia mencontohkan filsuf besar Martin Heidegger yang
mengatakan, “kebenaran adalah pengungkapan sesuatu yang membuat seseorang merasa pasti, jelas, serta kuat dalam tindakan maupun pengetahuannya.” Ia juga
mengatakan bahwa intelektual adalah “yang selalu mengambil tempat di sisi orang-orang yang kalah.”
Lebih lanjut, Edward W. Said, Guru Besar bahasa dan sastra
Universitas Columbia mengatakan “seorang intelektual adalah pencipta sebuah bahasa yang mengatakan yang benar kepada yang berkuasa, entah sesuai atau tidak dengan pikiran-pikiran pihak penguasa. Karena itu, ia lebih cenderung ke ‘oposisi’
daripada ke ‘akomodasi’.
Dosa paling besar seorang intelektual adalah apabila ia tahu apa yang seharusnya dikatakan tetapi menghindari mengatakannya. Ia hendaknya jangan sekali-kali mau mengabdi kepada mereka yang berkuasa.”
III. Epilog
Peran kaum intelektual Muslim sangat dibutuhkan kapanpun dan dimanapun,
terlebih lagi dalam menghadapi, sekularisme dan neo-feodalisme (neo-imperialisme)
di era neo-liberalisme saat ini. Kehadiran para intelektual Muslim bukan menjadi
milik siapa-siapa, dia tidak ‘menjual diri’ pada pihak manapun, namun dia
‘mewakafkan dirinya’ untuk kepentingan agama, bangsa dan negara.
Kehadiran intelektual Muslim sangat penting mengingat tantangan apakah umat
Islam mampu melakukan “hegemoni sosial” atau sebaliknya? ataukah “realitas sosial”
di luar Islam yang melakukan hegemoni atas Islam?. Tolok ukurnya adalah penerapan nilai-nilai syariat Islam dalam ‘kultural’ dan ‘struktural politik’.
Kaum intelektual Muslim yang konsisten sangat diperlukan sebagai “agent of change” dalam rangka mewujudkan transformasi menuju kemaslahatan berdasarkan
nila-nilai syariat Islam. Sebagai ‘agen perubahan’, intelektual Muslim harus mampu
mentransformasikannya dalam kehidupan sosial-keagamaan dan sekaligus dalam
struktur politik.
Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bish-shawab.